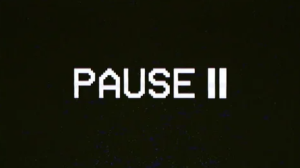Kita sering mengira menonton film adalah urusan yang selesai ketika lampu bioskop menyala. Atau ketika kredit akhir bergulir, film kita anggap berakhir. Kita berdiri, keluar dari ruang gelap, lalu kembali ke rutinitas.
Tapi bukankah terkadang tidak begitu?
Ada gambar yang tertinggal lebih lama dari durasi filmnya. Ada adegan yang ikut pulang bersama kita; bahkan ada yang terus tinggal di kepala dan perasaan kita. Di momen-momen seperti itu, kita mulai sadar: menonton film tidak sesederhana yang kita kira.
Film tidak pernah datang sendirian. Ia selalu hadir bersama ruang. Dan ruang itu selalu diisi oleh kita, penonton. Maka setiap pemutaran film, sekecil apa pun, sesungguhnya: sebuah pertemuan.
Film ≠ Cerita
Sering kali kita membicarakan film sebagai cerita. Kita menimbang alur, karakter, konflik, dan akhir. Semua itu penting. Namun ketika kita menonton film, yang berlangsung tidak hanya cerita.
Ada gambar yang berbicara lebih kuat daripada dialog. Ada jeda yang terasa ganjil; yang berlangsung sedikit lebih lama, tetapi justru menjadi bagian yang paling bermakna. Ada ritme yang membuat kita gelisah, atau sebaliknya, kelewat menenangkan sampai kita ketiduran.
Gilles Deleuze menyebut sinema sebagai pengalaman waktu. Film tidak selalu bergerak lurus ke depan. Kadang ia berhenti, melambat, berputar—bahkan berputar-putar. Di titik itu, kita tidak lagi sekadar mengikuti cerita, melainkan ikut mengalami waktu.
Sebuah film, sebelum ditonton, hanyalah kemungkinan. Ia baru hidup ketika seseorang hadir di hadapannya: duduk, diam, dan memberi perhatian.
Ruang Tidak Pernah Netral
Kita sering lupa bahwa tempat menonton ikut menentukan cara kita mengalami film.
Film yang sama bisa terasa berbeda ketika diputar di bioskop komersial, ruang komunitas, halaman sekolah, atau layar kecil di dalam rumah. Cahaya, tata suara, jarak dengan layar, hingga keberadaan orang lain; adalah prakondisi yang sering kali tidak kita sadari.
Ruang bukan sekadar tempat. Ia adalah bagian dari pengalaman itu sendiri.
Susan Sontag pernah mengingatkan bahwa sinema bukan hanya soal apa yang kita tonton, tetapi juga bagaimana dan di mana kita menontonnya. Ruang menentukan seberapa dekat kita dengan gambar, seberapa lama perhatian kita bertahan, dan apakah film itu memiliki cukup daya untuk tinggal di dalam diri kita atau cukup tak berdaya sehingga kita segera melupakannya.
Dalam konteks ini, ruang pemutaran alternatif tidak perlu diposisikan sebagai tandingan bioskop arus utama. Ia bisa dibaca sebagai kemungkinan lain bagi percakapan yang terjadi setelah lampu menyala.
Penonton Membawa Dirinya
Penonton bukanlah kertas yang bersih dan kosong.
Setiap orang datang dengan latar sosial, ingatan personal, referensi budaya, dan kondisi emosional yang berbeda. Dua orang menonton film yang sama, tetapi membawa pulang pengalaman yang berbeda.
Makna tidak sepenuhnya berada di dalam film. Ia lahir dari pertemuan antara film dan penontonnya di ruang tertentu, pada waktu tertentu. Karena itu, perbedaan bukan sesuatu yang harus dirapikan. Ia justru menandakan bahwa film itu hidup melalui perbedaan pengalaman dan pembacaan.
Roland Barthes pernah menulis tentang ruang bagi pembaca. Dalam sinema, ruang itu juga milik kita: penonton.
Kita bukanlah subjek pasif penerima makna, melainkan bagian dari proses pembentukannya.
Merawat Pemutaran = Merawat Pertemuan
Ketika film, ruang, dan penonton bertemu, ia selalu dipengaruhi oleh konteks yang lebih luas.
Siapa yang menonton? Film apa yang dipilih untuk diputar? Ruang seperti apa yang tersedia? Percakapan apa yang mungkin terjadi setelahnya?
Pertanyaan-pertanyaan ini sering luput, tetapi diam-diam menentukan wajah sinema dalam keseharian kita. Di titik inilah praktik kuratorial dan pemrograman menjadi penting—bukan sebagai penentu selera, melainkan sebagai upaya merawat pertemuan.
Mungkin dalam konteks itulah sinema terus hidup.